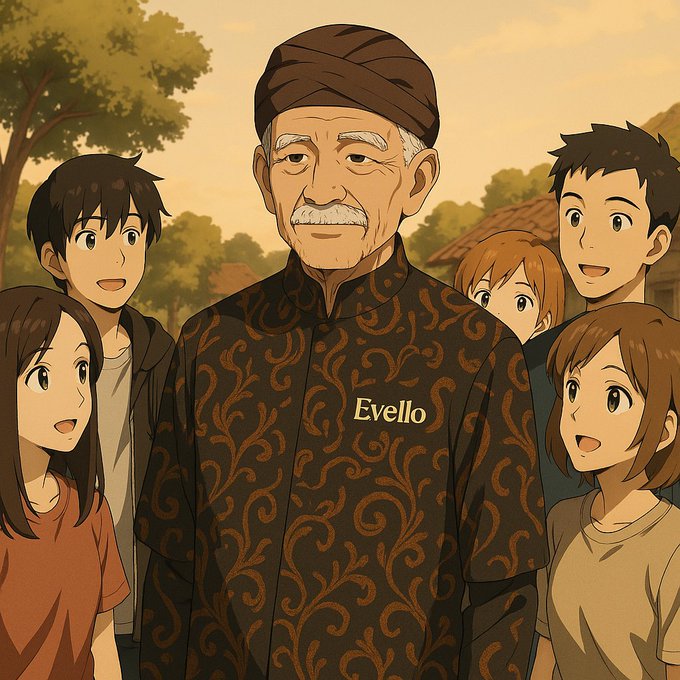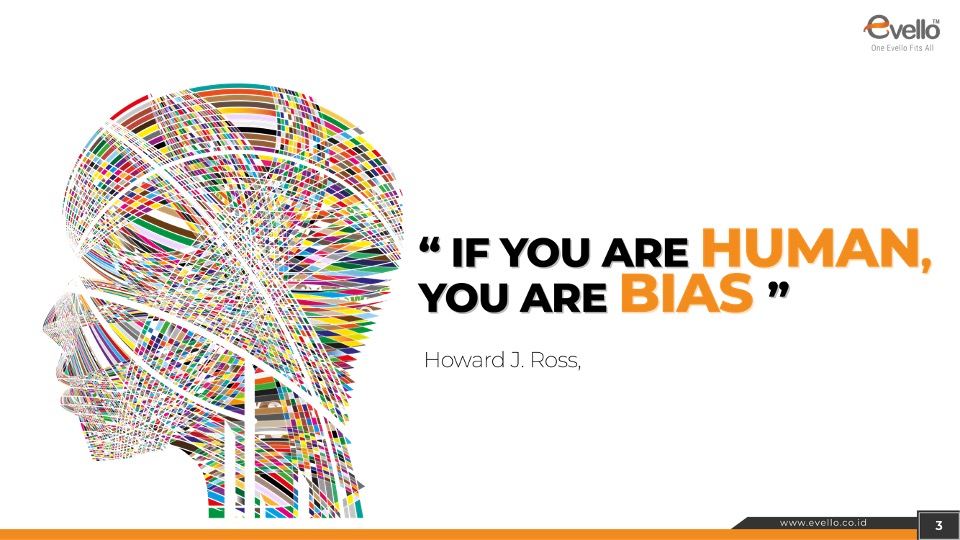Disadur dari buku @Evello12 tentang Cognitive Bias

Pagi di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, seperti biasa dipenuhi suara tawar-menawar, aroma rempah, dan langkah kaki yang tergesa. Di sudut warung kopi kecil yang nyempil di antara kios beras dan tukang tambal panci, tiga orang bapak-bapak duduk berbincang sambil menyeruput kopi tubruk panas.
Pak Udin yang mengenakan kopiah hitam dengan baju batik lawas duduk bersila, sesekali menyapu pandangan ke jalan pasar. Di sebelahnya ada Pak Rasta dan Pak Darsa, dua teman lamanya sejak zaman koperasi desa masih jadi pusat kegiatan warga.
“Jadi, kalian bakal pilih siapa nanti, Din?” tanya Pak Rasta sambil menepuk-nepuk kakinya. “Katanya sekarang banyak partai baru yang anak-anak muda bilang lebih jujur, lebih bersih. Partai hijau itu apa… Partai Perubahan? Yang itu tuh, yang calegnya mantan aktivis kampus.”
Pak Udin terkekeh, meletakkan gelas kopinya ke atas meja. “Ah, Rasta… kau mah dari dulu gitu. Tiap kali pemilu datang, selalu ngelirik partai baru. Saya mah, dari zaman dulu juga tetap Golkar. Udah terbukti.
Pak Darsa mengangguk pelan. “Betul. Saya juga masih ingat waktu Orba. Jalan dibangun, puskesmas ada, pupuk lancar. Itu semua waktu Golkar kuat. Sekarang mah partai baru cuma bisa ngomong doang, programnya bagus-bagus tapi belum tentu bisa jalan.”
Pak Rasta mencoba tersenyum, setengah ragu. “Tapi Din, jaman udah beda. Sekarang ini bukan cuma soal pengalaman, tapi soal siapa yang ngerti kondisi sekarang. Lihat aja tuh, yang muda-muda sekarang lebih milih partai yang ngajak diskusi, yang gak cuma bagi sembako.”
Pak Udin menyandarkan tubuhnya ke tiang kayu warung, matanya menerawang. “Saya bukannya gak ngerti, Ras. Tapi saya susah percaya sama partai yang baru muncul kemarin sore. Golkar itu udah seperti keluarga buat saya. Dari dulu, surat undangan kampung juga logonya Golkar. Yang bantu panen waktu paceklik juga orang-orang Golkar.”